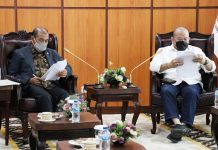Kolom Alif we Onggang
Cendekiawan?
Mungkin sekian lama jadi makhluk ‘alien’, — kita serta merta mendengar lagi kata cendekiawan, lantaran dalam satu dekade terakhir ini kita lebih kerap ditelikung pemimpin-pemimpin gadungan dan dikibuli politisi-politisi culun.
Cendekiawan adalah intelektual par exccellence — kastanya lebih tinggi ketimbang ilmuwan, — disegani saat Orde Baru begitu rupa dan lama menekan. Tertindas oleh rezim, justru Indonesia melahirkan cendekiawan-cendekiawan terkemuka yang, pemikirannya melampui zaman dan dihormati sedikitnya di kawasan Asia dengan warisan pikiran dan karya-karya bergizi.
Saat itu, mereka laksana penerang jalan di lorong gelap, namun, buat kekuasaan yang despotik ia dicap sebagai hantu yang menakutkan.
Ia seperti burung rajawali, dengan pandang visioner, bukan bebek yang bergerombol pada sebuah kepentingan. Ia tidak tersekat dalam satu himpunan. Cendekiawan adalah peran, bukan profesi yang memerlukan kode etik. Hidupnya asketis, independen dan bebas. Kekuatannya pada pikiran. Nlai-nilai etis melekat pada dirinya yakni moralitas, komitmen, integritas. Ia pembawa arah, memandu bangsanya agar tidak terserimpung dalam sirkus politik.
Tapi sekarang kemana mereka?
Jangan-jangan mereka duduk manis di menara gading menyaksikan cendekiawan-cendekiawan ‘tukang’ — biasa disebut cendekiawan organik; yang menghamba pada kekuasaan, atau jadi jongos komparador asing, kalau bukan pelindung kawanan oligarki. Jika begitu, mereka tak lebih dari cendekiawan yang berkhianat, sebagaimana pengingatan Julien Benda dalam La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Cendekiawan).
Kini, kita hidup di tengah disrupsi digital, — yang terjadi adalah debat pokrol bambu. Tidak sedikit cendekiawan memasuki arena politik memprovokasi kebencian dengan menjadikan diri mereka ideolog. Mereka tidak menjadi penengah yang berjarak pada kekuasaan. Karena afiliasi politik-lah para intelektual saling mencibir dan mencurigai. Demokrasi jadi sakit. Politik jadi panglima.
Salah kaprahnya, baru sahih dan hebat jika intelektual jadi politisi, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri. Iya kalau mengemban amanah. Bagaimana kalau ia menghabiskan sisa umurnya di terali besi?
Apa diperlukan lagi sebuah orde yang lebih tiranik supaya bangsa ini menelorkan cendekiawan-cendekiawan beken agar kita selamat dari perangkap pascakebenaran — post-truth ini?
Memang, satu dua buah pikir cendekiawan masih bisa diikuti, akan tetapi ia lebih merupakan khotbah moral ketimbang dialog publik sebagaimana antusiasme polemik kebudayaan pada 1935, debat ekonomi Pancasila dekade 80-an, lalu sastra kontekstual hingga persilangan pikir Islam Yes, Partai Islam No?
Saat ini atmosfer intelektual kita tampak redup. Tandanya, kita sulit menemukan buku-buku bernas, atau jurnal yang mewadahi pemikiran-pemikiran alternatif. Buku dilarang dan dibakar, tapi pikirannya tetap hidup. Ironisnya lagi, yang laris adalah buku-buku dengan topik banal: Jalur Cepat Masuk Surga, Menjadi Kaya Mendadak, Cara Bisnis Singkat Untuk Sukses, Pintar Bahasa Asing dalam Sehari. Semua serba pintas. Yang ada budaya instan.
Praktis kaum cedekiawan lebih gandrung mengunyah pemikiran dari planet lain, bukan yang mendasarkan pada pikiran sendiri. Padahal Indonesia dibangun oleh kekuatan pikiran, hibrida dari pelbagai gagasan dunia, dan jumputan dari kearifan lokal.
Dulu, para cerdik pandai menjadi begawan, melintasi semua genre ilmu, dengan bonus karya-karya fiksi yang mendunia, seturut Einstein, “imajinasi lebih kuat dari pengetahuan.” Sehingga banyak karya fiksi kaum cendekiawan Indonesia yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahkan ada karya kandidat Nobel — penghargaan prestisius bidang keilmuwan.
Jangan heran, Malaysia mendesakkan renungan cendekiawan kita dalam kurikulum pendidikannya. Setiap murid diwajibkan membaca karya masterpiece Indonesia untuk mengasah budi pekerti, menanamkan nilai-nilai humanisme dan spritual. Sementara di Indonesia siswa sebatas membuat sinopsis contekan.
Demikianlah, peradaban agung, pertama-tama dimulai dari kebiasaan catat mencatat, yang kelak dituangkan dalam karya tulis sebagai mercusuar peradaban.
Pengalaman mengasuh sebuah majalah dulu, setiap bulan ada utusan dari Kedubes Australia dan AS yang getol membeli majalah. Mereka ternyata memerlukan ‘harta tersimpan’, meski berupa percikan-nukilan pemikiran Nenek Mallomo, Amanna Gappa, Kajang, hingga cara ngeseks ala Bugis (assikalaibineng).
Bacaan yang lebih mirip stensilan ini lalu dikirim ke negaranya, dirawat seperti bayi dalam perpustakaan modern berpendingin, sementara di sini, ia menjadi alas pantat buat nonton layar tancap, atau sedikit lebih berguna jadi pembungkus gorengan.
Bukankah untuk menaklukkan sebuah bangsa ia harus lebih dulu mendalami budaya dan alam pikirnya?
Salah satu kelemahan kita adalah pengarsipan dan pendokumentasian, karena kentalnya budaya oral (lisan). Tak heran jika ingin mengulik alam pikir manusia Bugis Makassar, Mandar dan Toraja, kita mesti ke Belanda, Prancis, Australia, atau Amerika.
Karaeng Pattingalloang, cendekiawan Makassar abad 17, menguasai delapan bahasa asing, ahli matematika, dengan belasan ribu buku koleksinya, rajin menulis peristiwa, tapi kita belum menjumpai warisan catatannya. Padahal ratusan tahun sebelum Pattingalloang lahir, karya-karya al-Ghazali dan Aristoteles masih kita dapat baca hari ini.
Dan yang mencemaskan, minat baca Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara dunia. Budaya literasi belum tangguh, kita memasuki budaya penonton, lalu datang revolusi informasi, di mana orang lebih terpukau pada narasi-narasi di gawai yang mungkin saja meracuni otaknya. Tiba-tiba semua jadi pakar untuk semua hal. Tak ada lagi otoritas — ya si cendekiawan itu.
Sinergi Cendekiawan dan Saudagar
Sulawesi Selatan punya modal sosial sebagai ‘bangsa’ yang pernah memiliki puncak peradaban. Sejarawan Amerika Leonard Y Andaya kerap menyitir ‘Bangsa Bugis’, bukan suku — sepadan dengan bangsa India atau Cina sebagaimana tertulis dalam Sejarah Selat Malaka. Pun hanya segelintir suku yang memiliki aksara sendiri, dan kita punya Lontara.
Nenek moyang kita, 44 ribu tahun silam di situs Gua Leang Bulu Sipong Maros-Pangkep, sudah piawai melukis batu yang menggambarkan sebuah dongeng dan diklaim sebagai seni figuratif tertua di dunia yang dibikin manusia modern.
Pandai besi tertua dan terbaik di Asia Tenggara ada di Kerajaan Matano, Luwu Timur; pusat industri logam dan besi pada abad-8 Masehi, bahkan peneliti Belanda Van Heekeren bilang masyarakat di sana sudah melebur besi sejak 300 tahun sebelum Masehi.
Kitab magnum opus-nya orang Bugis masa pra-Islam, ialah I La Galigo yang mungkin sebagian besar buat kita acuh, namun oleh UNESCO ditahbiskan sebagai warisan dunia dan sastra klasik terpanjang yang pernah ada di Bumi.
Perahu pinisi juga diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dan simbol paling ikonik dalam sejarah maritim. Secara filosofis, pinisi merekatkan daerah-daerah yang terpisah-terserak oleh pulau-pulau, menjadi kesatuan NKRI.
Makassar abad 17 adalah kota kosmopolit di Asia Timur dan Tenggara, penduduknya multikultural, berinteraksi ke bangsa-bangsa asing, warga kotanya egaliter dan terbuka atas pandangan orang luar — bukan menyesatkan pikiran orang.
Sungguh dahsyat sekiranya cendekiawan bersinergi dengan para saudagar. Cendekiawan memproduk ilmu, saudagar yang merawat dan mengawetkannya dalam wujud pengadaan museum, perpustakaan, galeri, gedung kesenian (teater, film, tarian, orkestra) mendanai riset, menerbitkan buku, memberi beasiswa.
Gedung kesenian mementaskan I Tolok atau Samindara. I La Galigo tidak saja ditonton di Broadway, New York, sebagai pusat kebudayaan dunia, tapi di gedung teater di Makassar, Luwu atau Bone. Kita mendengar kelongkelonna anak mangkasara, atau sinrilik ketika disajikan di gedung opera, sesyahdu menikmati Mozart dan Beethoven di Gedung Opera Sydney. Dan orang-orang dari Barat datang ke Makassar menyaksikan drama musikal Kondo Buleng, atau Musik Tauriolo, karena seni itu abadi hidup itu singkat —ars longa vita brevis.-
Buku-buku cendekiawan Bugis Makassar, Mandar dan Toraja, tersaripati menjadi etos, jiwa, pandangan hidup, sebagaimana etika Protestan membangun Eropa, atau spirit Bushido memordenisasi Jepang. Terbayang mutiara pikiran para cendekiawan menjadi kurikulum pendidikan, lalu menginspirasi anak cucu menjadi manusia pembelajar. Siswa belajar keadilan dari Sultan Alauddin, belajar hukum ke Amanna Gappa, belajar agama dari Syekh Yusuf, belajar sastra dari Raja Ali Haji, belajar kearifan dari Arung Bila, belajar keberanian dari Karaeng Galesong.
Di perpustakaan, pikiran-pikiran hasil Pertemuan Cendekiawan Bugis Makassar, bisa diserap kembali di situ, meski kita sudah tiada, tapi ‘ilmu’ dan spiritnya terus menyala, hidup ribuan tahun, entah itu pappaseng, kata-kata bijak bestari dari Lontara, dan pesan-pesan moral lokal genius lainnya.
Dari mutiara ini bisa membentuk jiwa, mengasah akal, mengolah rasa, menajamkan nalar, menjadi manusia-manusia unggul: macca, malempu, warani, magetteng.
Gokil, kata anak milineal.
Tapi, kalau kita abai, maka kita menanggung dosa, apalagi mengambil prinsip eja tompi nadoang. Kalau begitu, peradaban kita yang selama ini diagung-agungkan Barat, cuma untuk romantisme doang, dan boleh jadi punah menyusul peradaban peradaban kuno yang raib terkubur sejarah.